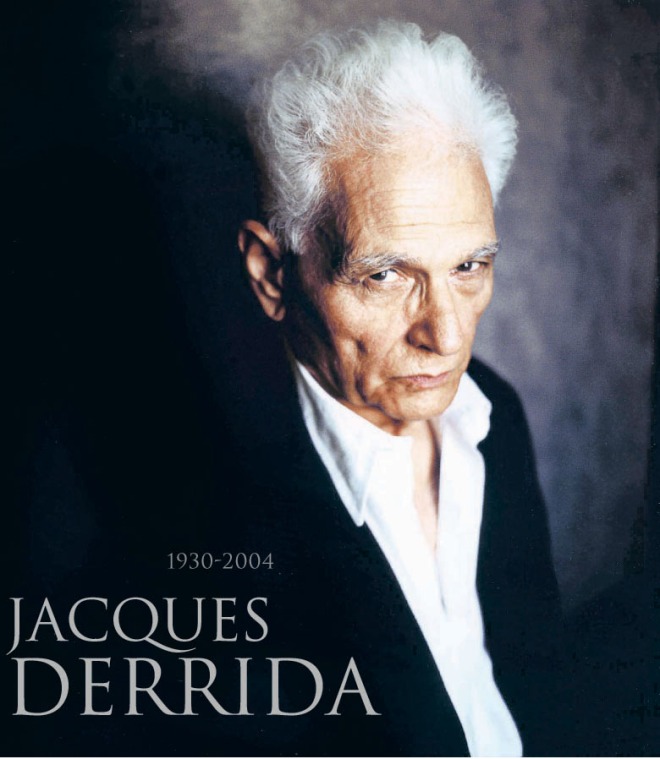Enam Definisi Hermeneutika
Reza A.A Wattimena
Definisi hermeneutika masihlah terus berkembang. Menurut Richard E. Palmer, definisi hermeneutika setidaknya dapat dibagi menjadi enam. Sejak awal, hermeneutika telah sering didefinisikan sebagai ilmu tentang penafsiran (science of interpretation).[1] Akan tetapi, secara luas, hermeneutika juga sering didefinisikan sebagai, pertama, teori penafsiran Kitab Suci (theory of biblical exegesis). Kedua, hermeneutika sebagai metodologi filologi umum (general philological methodology). Ketiga, hermeneutika sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa (science of all linguistic understanding). Empat, hermeneutika sebagai landasan metodologis dari ilmu-ilmu kemanusiaan (methodological foundation of Geisteswissenschaften). Lima, hermeneutika sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi (phenomenology of existence dan of existential understanding). Dan enam, hermeneutika sebagai sistem penafsiran (system of interpretation). Hermeneutika sebagai sistem penafsiran dapat diterapkan, baik secara kolektif maupun secara personal, untuk memahami makna yang terkandung dalam mitos-mitos ataupun simbol-simbol.
Keenam definisi tersebut bukan hanya merupakan urutan fase sejarah, melainkan pendekatan yang sangat penting didalam problem penafsiran suatu teks. Keenam definisi tersebut, masing-masing, mewakili berbagai dimensi yang sering disoroti dalam hermeneutika. Setiap definisi membawa nuansa yang berbeda, namun dapat dipertanggungjawabkan, dari tindakan manusia menafsirkan, terutama penafsiran teks.[2] Tulisan ini mau memberikan kerangka menyeluruh tentang keenam definisi tersebut, yang lebih banyak berfungsi sebagai pengantar pada arti sesungguhnya dari hermeneutika.
Teori Penafsiran Kitab Suci
Pengertian tertua, dan mungkin yang paling banyak dipahami oleh banyak orang, adalah hermeneutika sebagai prinsip-prinsip penafsiran kitab suci (principles of biblical interpretation). Ada pembenaran yang bersifat historis terhadap pemahaman ini, karena kata hermeneutika pada era modern memang digunakan untuk mengisi kebutuhan akan panduan dalam penafsiran Kitab Suci. Akan tetapi, hermeneutika bukanlah isi penafsiran, melainkan metodenya. Perbedaan antara penafsiran aktual (exegesis) dan aturan-aturan, metode-metode, dan teori yang mengaturnya (hermeneutika) sudah sejak lama disadari, baik didalam refleksi teologis, dan kemudian didalam refleksi-refleksi non teologis.
Di Inggris, dan nantinya di Amerika, penggunaan kata hermeneutika mengikuti kecenderungan umum yang mengacu pada penafsiran kitab suci. Penggunaan pertama, setidaknya yang terdokumentasikan, dapat dilihat di Oxford English Dictionary pada 1737, yakni “mengambil kebebasan dengan tugas khusus yang suci, yang juga berarti melakukan tugas-tugas yang adil dan hermeneutika yang bijaksana.”[3]
Ketika penggunaan kata hermeneutika meluas pada teks-teks non kitab suci, biasanya teks tersebut sangatlah sulit untuk dimengerti, sehingga membutuhkan metode khusus untuk mengerti makna yang tersembunyi. Salah satu bentuk hermeneutika non kitab suci dirumuskan oleh Edward Burnett Taylor pada Primitive Culture (1871). Ia menulis, “Tidak ada legenda, tidak ada alegori, tidak rima, yang tidak membutuhkan hermeneutika untuk mengerti mitologi-mitologi.”[4] Dengan demikian, seperti sudah disinggung sebelumnya, penggunaan kata hermeneutika pada bidang-bidang non kitab suci seringkali ditujukan pada teks-teks yang memiliki makna tersembunyi yang sulit dimengerti, sehingga membutuhkan penafsiran khusus untuk menangkap makna tersebut.
Kata hermeneutika biasanya sering ditarik genesisnya sampai abad ke-17. Akan tetapi, proses menafsirkan, baik itu dalam bentuk penafsiran religius, sastra, maupun bahasa-bahasa hukum, dapat dirunut langsung kejaman Yunani maupun Romawi Kuno. Sejarahnya bisa dirunut sampai panjang sekali. Kedetilan historis semacam itu tidak dapat dipresentasikan disini. Akan tetapi, ada dua butir refleksi yang kiranya bisa berguna untuk kita, yakni akar hermeneutik yang sebenarnya bisa ditemukan dalam proses penafsiran Kitab Suci, dan pertanyaan lainnya yang mencangkup keluasan bidang refleksi hermeneutika.
Tanpa bermaksud untuk terjebak dalam detil, adalah penting bagi kita untuk mencatat, bahwa ada kecenderungan umum di dalam metode penafsiran Kitab Suci untuk menggunakan “sistem” penafsiran, di mana penafsiran difokuskan dengan satu metode tertentu yang telah diakui bersama. “Sistem” semacam itu seringkali dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai kerangka panduan. Suatu teks tidak dapat ditafsirkan dengan bersandar pada teks itu sendiri, karena hal tersebut tidaklah mungkin. Suatu teks hanya bisa ditafsirkan di bawah pengaruh semangat jaman tertentu. Misalnya, penafsiran teks-teks Kitab Suci pada jaman Pencerahan cenderung optimistik terhadap kebebasan manusia dan memuat nilai-nilai moral yang juga bersifat optimistis. Dalam arti ini, hermeneutika adalah cara ataupun metode sang penafsir untuk menemukan makna tersembunyi di dalam teks.
Pertanyaan lain banyak berkaitan dengan keluasan dan ruang lingkup hermeneutika. Dalam hal ini, setidaknya ada pendapat yang saling berdebat satu sama lain, yakni disatu sisi ada pendapat yang melihat bahwa hermeneutika haruslah merumuskan sebuah teori yang eksplisit sebagai panduan dalam menafsirkan teks, dan disisi lain ada pendapat yang melihat bahwa metode hermeneutika haruslah tidak dirumuskan secara eksplisit, melainkan implisit dan terwujud di dalam praksis penafsiran yang dikaitkan dengan pengaruh-pengaruh lainnya. Misalnya, seorang teolog yang bernama Gerard Ebeling tengah melakukan studi tentang “hermeneutika Luther”. Dalam hal ini, apakah ia harus memfokuskan diri untuk tetap pada analisa persepsi Luther tentang penafsiran, atau ia harus juga menempatkan tesis Luther tentang hermeneutika dengan tulisan-tulisan Luther yang lainnya? Ebeling melakukan keduanya. Masalahnya, apakah metode yang ia gunakan tersebut harus dalam bentuk-bentuk prinsip yang jelas berkaitan dengan tesis hermeneutika yang dirumuskan Luther, ataukah biarkan metode tersebut mewujud di dalam praktek penafsiran yang melibatkan berbagai aspek lain, yang mungkin mempengaruhi cara Luther merumuskan tesis hermeneutikanya. Yang paling baik memang menggabungkan keduanya, seperti yang dilakukan oleh Ebeling.
Dengan demikian, di dalam tegangan antara metode hermeneutika yang eksplisit fokus pada satu fenomen, atau pada metode hermeneutika yang mau menangkap yang tersembunyi di balik fenomen-fenomen lainnya, yang mungkin mempengaruhi fenomen yang ingin dianalisa, hermeneutika dan pemahaman yang mendalam tentangnya, baik secara epistemologis maupun ontologis, adalah sangat penting untuk mencari pengertian yang lebih dalam tentang cara manusia menafsirkan dirinya, maupun menafsirkan “dunianya”.
Metodologi Filologi
Perkembangan rasionalisme pada abad ke-18 juga berpengaruh pada pemahaman tentang hermeneutika. Hermeneutika pun, yang tadinya hanya digunakan di dalam proses penafsiran Kitab Suci, ternyata juga dapat diterapkan pada bidang-bidang lainnya, yang non Kitab Suci. “Norma-norma penafsiran Kita Suci”, demikian tulis Spinoza, “hanya dapat menjadi cahaya bagi rasionalitas yang cocok untuk semua.”[5]
Tantangan untuk menerapkan metode hermeneutika pada bidang-bidang non Kitab Suci. Yang menjadi penting disini adalah, bahwa sang penafsir tidak lagi hanya menarik nilai-nilai moral dari suatu teks, tetapi juga mampu memahami “roh” yang berada di balik teks, dan kemudian menterjemahkannya secara rasional sesuai konteks yang berlaku. Banyak ahli yang berpendapat, bahwa pemahaman semacam merupakan proses demitologisasi gerakan pencerahan atas teologi dan agama-agama. Walaupun, terutama di abad ke-20, proses tersebut tidak lagi dipahami sebagai pemurnian tafsiran dari mitos, dan kemudian menjadikannya serasional mungkin, tetapi lebih sebagai proses penafsiran lebih jauh dari penafsiran yang sudah ada sebelumnya.[6]
Sebagai fungsi metodologi filologi, hermeneutika menuntut sang penafsir untuk mengerti latar belakang sejarah dari teks yang ditafsirkannya. “Setiap penafsir”,tulis J.S Semler,”haruslah mampu berbicara tentang teks yang ditafsirkannya dengan cara yang sesuai dengan jaman yang berbeda, serta situasi yang berbeda…”[7] Dengan demikian, seorang penafsir juga adalah seorang “sejarahwan”, yang mampu mengerti dan memahami “roh” historis dari teks yang dianalisanya, sehingga makna yang tersembunyi dapat terungkap.
Ilmu Pemahaman Bahasa
Dalam bidang ini, filsuf yang banyak memberikan kontribusi adalah Schleiermacher. Ia memandang hermeneutika sebagai semacam sintesa antara “ilmu” sekaligus “seni” untuk memahami. Pemahaman semacam ini mau melampaui konsep, yang melulu memandang hermeneutika sebagai kelompok aturan koheren dan sistematis, yang merupakan panduan utama untuk menafsirkan teks. Schleiermacher tidak puas hanya dengan memandang hermeneutika sebagai metodo filologi, seperti yang sedikit sudah dijelaskan di atas, melainka juga melihat hermeneutika sebagai “hermeneutika umum”.[8] Prinsip-prinsip hermeneutika umum dapat juga berfungsi sebagai landasan atas berbagai macam penafsiran teks.
Dengan merumuskan hermeneutika sebagai “hermeneutika umum”, ia, untuk pertama kalinya, memahami hermeneutika sebagai studi atas pemahaman itu sendiri. Hermeneutika semacam ini merupakan semacam sintesa antara tafsir Kitab Suci dan Filologi.
Landasan Metodologis bagi Ilmu-ilmu Kemanusiaan
Wilhelm Dilthey, satu filsuf yang banyak berbicara tentang hermeneutika pada abad ke-19, berpendapat, bahwa hermeneutika adalah displin berpikir, yang dapat digunakan sebagai landasan metodologi untuk ilmu-ilmu kemanusiaan, yakni ilmu-ilmu yang memfokuskan analisanya pada pemahaman akan seni, tindakan sosial manusia, maupun karya-karyanya.
Menurutnya, untuk menafsirkan dan memahami ekspresi dari karya-karya manusia, terutama dalam bentuk karya-karya sastra, penafsiran Kitab Suci, dan penafsiran hukum, diperlukan tindakan pemahaman sejarah, yang secara operasional berbeda dengan metode sains yang kuantitatif untuk memahami gejala-gejala alam. Ia berpendapat bahwa di dalam ilmu-ilmu kemanusiaan diperlukan “rasionalitas” yang lain untuk memperoleh pemahaman sejarah, yang berbeda dari “rasionalitas murni” Kantian, yang dapat digunakan untuk menafsirkan alam. Jenis “rasionalitas” untuk memperoleh pemahaman di dalam ilmu-ilmu kemanusiaan adalah “rasionalitas historis”.
Hermeneutika, bagi Dilthey, adalah displin ilmu yang berfokus pada problem penafsiran, dan terutama sekali adalah penafsiran atas obyek-obyek historis, yakni sebuah teks. Oleh karena itu, metode yang paling tepat adalah memahami, dan bukan mengkalkulasi secara kuantitatif, seperti yang diterapkan pada ilmu-ilmu alam. Dalam hal ini, ia telah merumuskan landasan yang lebih manusiawi dan historis tentang metodologi ilmu-ilmu kemanusiaan.
Fenomenologi Dasein dan Pemahaman Eksistensial
Berbicara tentang Dasein berarti kita harus berbicara tentang Martin Heidegger. Untuk merefleksikan berbagai problem metafisika, ia menggunakan fenomenologi, seperti yang telah dirumuskan oleh Edmund Husserl. Heidegger melakukan studi fenomenologi atas keseharian manusia di dunia. Studinya tersebut ada pada buku Being and Time (1927), yang merupakan karya Magnus Opusnya. Dalam bukunya tersebut, ia melakukan refleksi atas (manusia) Dasein, yang disebutknya sebagai hermeneutika atas Dasein.
Dalam konteks ini, hermeneutika tidaklah diartikan sebagai ilmu ataupun aturan tentang penafsiran teks, atau sebagai metodologi ilmu-ilmu kemanusiaan, tetapi sebagai eksplisitasi eksistensi manusia itu sendiri. Heidegger berpendapat bahwa “penafsiran” dan “pemahaman” merupakan modus mengada manusia. Dengan demikian, hermeneutika Dasein dari Heidegger, terutama selama berupaya merumuskan ontologi dari pengertian, jugalah merupakan hermeneutika. Ia merumuskan metode khusus hermeneutika untuk menafsirkan Dasein secara fenomenologis.
Hans-Georg Gadamer mengembangkan implikasi lebih jauh dari hermeneutika Haidegger di dalam sebuah karya sistematik, yang berjudul “Philosophical Hermeneutics”(Truth and Method). Di dalam buku itu, ia merunut perkembangan hermeneutika secara detil mulai dari Schleiermacher, Dilthey, sampai pada Heidegger. Akan tetapi, Truth and Method lebih dari sekedar sejarah hermeneutika, melainkan juga sebuah upaya untuk mengkaitkan hermeneutika dengan estetika, dan juga sebuah refleksi filsafat “pemahaman sejarah” (historical understanding). Ia juga menjabarkan kritik Heidegger terhadap hermeneutika, dan kemudian merumuskan konsep “kesadaran yang bergerak dalam sejarah”, seperti yang pernah juga dirumuskan oleh Hegel, bahwa penafsiran bergerak secara dialektis bersama sejarah, dan kemudian ditampilkan di dalam teks.
Gadamer dan Heidegger mengangkat hermeneutika sampai pada level “linguistik”, di mana Ada sesungguhnya hanya dapat dimengerti melalui bahasa. Hermeneutika adalah pertemuan sang penafsir dengan Ada melalui bahasa. Dengan demikian, mereka memberikan arti lain bagi kata hermeneutika, yakni sebagai problem filosofis tentang relasi antara bahasa dengan Ada, pemahaman manusia, sejarah, eksistensi, dan realitas. Hermeneutika pun ditempatkan sebagai salah satu refleksi filsafat yang cukup sentral dewasa ini, yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ontologis maupun epistemologis, karena proses manusia memahami itu sendiri adalah persoalan ontologis dan epistemologis.
Sistem Interpretasi
Paul Ricoeur mau mendefinisikan hermeneutika dengan kembali pada analisis tekstual, yang memiliki konsep-konsep distingtif serta sistematis. “Yang saya maksudkan dengan hemeneutika,” demikian tulis Ricoeur, “adalah peraturan-peraturan yang menuntun sebuah proses penafsiran, yakni penafsiran atas teks partikular atapun kumpulan tanda-tanda yang juga dapat disebut sebagai teks…”[9] Psikoanalisis, terutama dalam tafsir mimpi, jelas merupakan proses hermeneutika. Semua aspek tentang hermeneutika ada di sana. Mimpi menjadi teks. Teks tersebut mempunyai berbagai bentuk simbol, dan sang analis akan menggunakan simbol-simbol tersebut untuk menafsirkan dan mengungkapkan makna yang tersembunyi. Dalam konteks ini, hermeneutika adalah suatu cara untuk menangkap makna yang masih bersifat implisit di dalam mimpi, dan yang sesungguhnya mempunyai arti penting. Obyek dari penafsiran, yakni teks dalam arti seluas-luasnya, juga bisa merupakan simbol yang terdapat di dalam mimpi, simbol yang terdapat pada sebuah tulisan, ataupun di dalam masyarakat itu sendiri.
Ricoeur membedakan dua macam simbol, yakni simbol univokal dan simbol ekuivokal. Simbol univokal adalah simbol dengan satu makna, seperti pada simbol-simbol logika. Sementara itu, simbol ekuivokal, yang merupakan perhatian utama dari hermeneutika, yang simbol yang memiliki bermacam-macam makna. Heremeneutika haruslah berhadapan dengan teks-teks simbolik, yang memiliki berbagai macam makna. Hermeneutika juga haruslah membentuk semacam kesatuan arti yang koheren dari teks yang ditafsirkan, dan sekaligus memiliki relevansi lebih dalam serta lebih jauh untuk masa kini maupun masa depan. Dengan kata lain, hermeneutika merupakan sebuah sistem penafsiran, di mana relevansi dan makna lebih dalam dapat ditampilkan melampaui sekaligus sesuai dengan teks yang kelihatan.
Upaya untuk menemukan makna tersembunyi di dalam mimpi, ataupun di dalam “simbol” yang tampak tidak berkaitan satu sama lain menunjukkan satu hal, yakni bahwa realitas yang tampak di depan mata kita ini sesungguhnya tidaklah dapat dipercaya. Freud memberikan sumbangan yang penting sekali tentang hal ini. Ia mengajarkan kepada kita untuk tidak begitu saja percaya terhadap apa yang kita sebut sebagai pengetahuan sebagai hasil dari kesadaran. Dengan bertitik tolak dari situ, ia pun mengajak kita untuk menghantam semua bentuk mitos dan ilusi, yang mungkin selama ini telah kita pahami sebagai pengetahuan hasil dari kesadaran. Salah satu yang ingin ditunjukkan Freud adalah agama sebagai mitos dan ilusi manusia. Agama adalah ilusi orang-orang yang tidak dewasa. Dalam hal ini, fungsi hermeneutika kritis Freud bersifat kritis.
Berbagai bentuk cara penafsiran yang dapat dilakukan manusia itulah yang mendorong Ricoeur untuk merumuskan dua macam bentuk hermeneutika, yakni yang pertama hermeneutika sebagai upaya penafsiran untuk menangkap makna tersembunyi di dalam suatu teks ataupun simbol, dan kedua, hermeneutika sebagai cara untuk bersikap kritis dan kemudian menghancurkan semua bentuk ilusi ataupun kesadaran palsu, yang mungkin muncul akibat simbol-simbol atau teks tertentu. Bentuk kedua ini disebut juga sebagai hermeneutika “demistifikasi”. Ia kemudian menunjuk beberapa pemikir, yang dianggapnya sebagai filsuf demistifikasi, yakni Nietzsche, Freud, dan Marx. Ketiga orang ini berpendapat, bahwa realitas yang tampak di depan mata kita itu palsu dan menindas. Mereka kemudian merumuskan sebuah alternatif berpikir untuk membuka dan melawan kepalsuan tersebut, karena kepalsuan tersebut memiliki ekses-ekses yang menghambat kehidupan manusia. Mereka juga mengganggap agama sebagai salah satu bentuk mitos dan ilusi, yang harus dikupas dan dilawan. Cara berpikir yang benar adalah cara berpikir yang selalu memandang sesuatu secara kritis, yakni dengan penuh kecurigaan dan keraguan. Dengan cara berpikir seperti itu, perubahan sosial ke arah pembebasan manusia dapatlah diwujudkan. Penafsiran yang mengarahkan dirinya pada arah pembebasan. Ini adalah suatu bentuk hermeneutika yang baru.
Dengan begitu banyak metode yang dapat digunakan di dalam hermeneutika, Ricoeur berpendapat bahwa tidak ada satu bentuk norma universal di dalam penafsiran manusia, melainkan teori-teori yang terpisah, dan saling berdebat satu sama lain.[10] Akan tetapi, setidaknya ada dua bentuk besar dari metode hermeneutika ini. Di satu sisi, ada para penafsir yang melihat teks dan simbol sebagai sesuatu yang sakral, dan berupaya untuk menafsirkan yang sakral tersebut untuk menemukan makna yang tersembunyi di baliknya. Di sisi lain, ada para penafsir yang bahwa simbol dan teks adalah sebuah realitas yang palsu, yang harus dikupas struktur-struktur menindasnya.
Penafiran Ricoeur atas teks-teks Freud sendiri adalah suatu bentuk penafsiran kreatif yang mengagumkan. Ia membaca Freud, menafsirkannya, dan menemukan relevansinya bagi kehidupan masa kini maupun untuk masa depan. Ia mau merumuskan suatu bentuk hermeneutika, di mana rasionalitas dalam bentuk keraguan dan kecurigaan dapat dipadukan dengan interpretasi reflektif untuk menemukan makna tersembunyi di balik teks ataupun simbol tertentu. Sekarang ini, filsafat banyak berupaya menafsirkan bahasa. Hermeneutika, seperti yang telah disintesakan oleh Ricoeur, ditantang untuk menafsirkan bahasa secara kreatif tanpa terjatuh mengganggapnya sebagai sesuatu yang sakral, ataupun melulu dicurigai sebagai ilusi atau mitos yang menindas.
Menafsirlah secara kreatif!
Daftar Pustaka
Richard E. Palmer, Hermeneutics, Northwestern University Press, 1969.
[1] Lihat, Richard E. Palmer, Hermeneutics, Northwestern University Press, 1969, hal. 33.
[2] Ibid, hal. 34.
[3] Ibid, hal.35.
[4] Primitive Culture, hal. 319, dalam Palmer, ibid.
[5] Spinoza, Tractatus theologico-politicus, bab 7, seperti dikutip Palmer, 1969.
[6] Palmer, 1969, hal. 39.
[7] Lihat, Kraus, hal. 93-102, dalam Palmer, 1969.
[8] Lihat Palmer,1969, hal. 40.
[9] Ibid, hal. 43.
[10] Ibid, hal. 44.