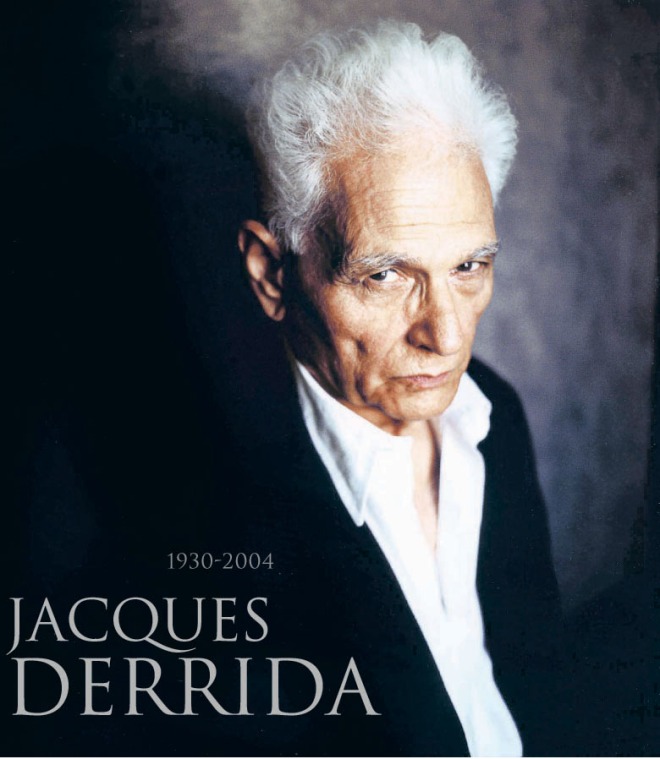Filsafat Kritis Kant
Reza A.A Wattimena
Pada bab sebelumnya saya sudah membahas mengenai metode skeptik yang kental di dalam filsafat modern. Filsuf yang secara khusus menggunakan metode ini adalah Rene Descartes dan David Hume. Inti dari skeptisisme adalah kecurigaan terhadap semua bentuk klaim pengetahuan tertentu. Dengan metode skeptisismenya filsafat modern mengajarkan kita untuk berani berpikir kritis untuk menantang semua klaim kebenaran dan pengetahuan yang muncul. Tujuannya adalah supaya kita bisa hidup dengan berpegang pada kebenaran yang otentik, dan bukan pada keyakinan-keyakinan tanpa dasar.
Melanjutkan ‘seni untuk memahami realitas’ di dalam filsafat modern, saya ingin mengajak anda mencecap metode berpikir yang digunakan oleh Immanuel Kant di dalam filsafatnya. Sebagai teks pembantu saya menggunakan dua teks, yakni tulisan Jill Vince Buroker yang berjudul Kant’s Critique of Pure Reason dan tulisan saya sendiri dalam bentuk tesis S2 yang berjudul Pengandaian-pengandaian Metafisis di dalam Kritik Immanuel Kant terhadap Metafisika: Mempertimbangkan Kritik Karl Ameriks atas Kritik Immanuel Kant terhadap Metafisika.[1]
Proyek Kritik Kant
Tujuan utama dari filsafat kritis Kant adalah untuk menunjukkan, bahwa manusia bisa memahami realitas alam (natural) dan moral dengan menggunakan akal budinya. Pengetahuan tentang alam dan moralitas itu berpijak pada hukum-hukum yang bersifat apriori, yakni hukum-hukum yang sudah ada sebelum pengalaman inderawi. Pengetahuan teoritis tentang alam berasal dari hukum-hukum apriori yang digabungkan dengan hukum-hukum alam obyektif. Sementara pengetahuan moral diperoleh dari hukum moral yang sudah tertanam di dalam hati nurani manusia. Kant menentang empirisme dan rasionalisme. Empirisme adalah paham yang berpendapat, bahwa sumber utama pengetahuan manusia adalah pengalaman inderawi, dan bukan akal budi semata. Sementara rasionalisme berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan adalah akal budi yang bersifat apriori, dan bukan pengalaman inderawi. Bagi Kant kedua pandangan tersebut haruslah dikombinasikan dalam satu bentuk sintesis filosofis yang sistematis.[2]
Kant juga berpendapat bahwa moralitas memiliki dasar pengetahuan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan (science). Oleh karena itu ia kemudian menulis Groundwork of the Metaphysics of Morals pada 1785, dan Critique of Practical Reason pada 1788. Pada 1790 Kant menulis Critiqe of the Power of Judgment. Di dalamnya ia menyentuh bidang estetika. Namun pada hemat saya, metode di dalam filsafat kritis Kant lebih nyata di dalam bukunya yang pertama, yakni Critique of Pure Reason yang saya terjemahkan menjadi Kritik atas Rasio Murni. Buku inilah yang kemudian menjadi acuan saya dan Buroker pada bab ini.
Di dalam bagian pengantar dari Kritik atas Rasio Murni, Kant menyatakan bahwa “walaupun metafisika banyak dimaksudkan sebagai ratu dari ilmu-ilmu,[3] tetapi rasionalitas metafisis kini dihadapkan pada sebuah pengadilan.”[4] Sekali lagi, “kita harus menelusuri kembali langkah-langkah yang telah kita rumuskan.”[5] Perdebatan di dalam refleksi metafisika telah membuat metafisika itu sendiri menjadi semacam medan pertempuran, di mana setiap pihak yang berperang tidak berhasil mendapatkan satu inci pun dari ‘teritori’ yang ada.[6] Konsekuensinya metafisika kini ‘terombang ambing’ di antara dogmatisme dan skeptisisme. Metafisika telah menjadi pemikiran spekulatif yang meraba-raba secara acak.[7]
Melawan kecenderungan perdebatan metafisika pada jamannya itu, Kant merumuskan semacam Revolusi Copernican di dalam filsafat.
“Selama ini telah diasumsikan bahwa semua pengetahuan kita harus menyesuaikan dirinya dengan obyek. Akan tetapi, sejak asumsi ini telah gagal menghasilkan pengetahuan metafisis, kita harus melakukan semacam penilaian apakah kita tidak akan lebih berhasil di dalam metafisika, …. Jika kita mengasumsikan bahwa obyeklah yang harus menyesuaikan diri dengan kesadaran kita…. Kita harus memulai tepat pada garis di mana hipotesis utama Copernicus bermula, yakni hipotesis tentang heliosentrisme…”[8]
Untuk menjelaskan latar belakang pemikiran Kant, pada sub bab ini, saya hendak memaparkan latar belakang historis dan epistemologis sebagai konteks kritiknya terhadap metafisika tradisional.[9] Kerangka tulisan di dalam sub bab ini diinspirasikan dari pembacaan saya terhadap tulisan Sebastian Gardner.
Latar Belakang Historis: Refleksi Filsafat di Abad Pencerahan
Filsafat Kant dirumuskan dalam perdebatan dua pandangan besar pada waktu itu, yakni rasionalisme dan empirisme, khususnya rasionalisme G.W. Leibniz (1646-1716), dan empirisme David Hume (1711-1776). Kant dipengaruhi oleh mereka, tetapi mengkritik kedua pemikiran filsuf ini untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan mereka, serta kemudian merumuskan pandangannya sendiri sebagai sintesis kritis dari keduanya, yakni filsafat transendental (transcendental philosophy). Dalam arti yang lebih luas, ia mau ‘melampaui’ posisi epistemologis dua paradigma yang saling beroposisi tersebut. Ini adalah intensi utama dari filsafat Kant, yakni sebuah tanggapan terhadap problem epistemologis yang terkait dengan proyek pencerahan yang mendominasi panggung filsafat abad ke delapan belas.
Seperti lazimnya di dalam perumusan sejarah pemikiran, kesatuan ide pada Abad Pencerahan, atau yang banyak dikenal sebagai abad rasionalitas, hanya dapat dilihat tesis-tesis utamanya yang paling mendasar saja. Tentu saja masa itu penuh dengan ide-ide yang saling bertentangan yang tidak dapat begitu saja dirumuskan dalam satu tesis yang mau mencakup semuanya. Atas dasar itu dapat juga dikatakan, bahwa Pencerahan mengambil inspirasi utamanya dari kesuksesan revolusi sains pada abad XVI-XVII, serta untuk memperjuangkan apa yang sekarang ini telah dianggap ‘biasa’, yakni hak setiap orang untuk berpikir sendiri tentang hal-hal praktis maupun teoretis lepas dari tradisi atau otoritas eksternal tertentu. Rasionalitas sudah ada inheren di dalam diri manusia, dan tinggal digunakan untuk mencerahkan kehidupan sehari-hari mereka. Para pemikir Pencerahan hendak mempromosikan institusi sosial politik yang menghormati otonomi setiap orang, mendorong penelitian-penelitian saintifik, dan menunjang peningkatan pengetahuan pada umumnya. Asumsi mereka dari emansipasi intelektual, maka emansipasi politik akan terjadi. Pencerahan adalah seperti yang dirumuskan dalam sebuah esei untuk mendefinisikan hal tersebut, kemunculan manusia dari ketidakdewasaan yang dibuatnya sendiri. Semboyan utamanya adalah ‘Sapere Aude’ (Beranilah Berpikir Sendiri!). Seperti dikutip oleh Gardner, Kant menulis,
“Masa dimana kita hidup adalah, dalam arti khusus, masa kritisme, dan untuk mengkritik apapun yang ada. Termasuk diantaranya adalah agama dengan kesuciannya, hukum yang telah terberi dengan kemuliaannya… haruslah mampu bertahan di hadapan ujian akal budi yang bebas dan terbuka.”[10]
Lebih jauh lagi para pemikir Pencerahan sangatlah yakin bahwa kemajuan sudah merupakan bagian inheren di dalam karakter manusia itu sendiri, terutama kemajuan di dalam memahami dunianya melalui sains dan teknologi, seperti pada pencapaian luar biasa yang dirumuskan oleh Isaac Newton (1642-1727). Lambang kemajuan lainnya adalah semakin berkembangnya toleransi di dalam maupun maupun di antara agama-agama, semakin lenyapnya otoritas mutlak Gereja, perubahan tatanan sosial-politik yang berjalan paralel dengan perkembangan kaum borjuis, dan semakin runtuhnya tirani cara berpikir metafisis-religius yang banyak dikembangkan pada Abad Pertengahan. Semua hal ini menunjukkan bahwa sejarah telah bergerak ke arah kemajuan total yang tidak bisa lagi dihentikan oleh apapun atau siapapun.
Secara umum Jerman tempat Kant lahir dan tinggal seumur hidupnya tidak berpartisipasi secara aktif di dalam proses Pencerahan. Proses pencerahan itu sendiri lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke (1632-1704) dan Newton. Para pemikir yang juga cukup berpengaruh pada masa itu adalah David Hume dan Adam Smith (1723-1790). Pada pertengahan abad ke-18, pusat gerakan pencerahan ini adalah Perancis, terutama di kalangan para pemikir Encyclopedie, di mana Denis Diderot dan Jean d’Alembert menjadi tokohnya. Banyak pemikir lain juga yang memberikan sumbangan besar bagi perkembangan mazhab tersebut. Mereka disebut The Philosophes. Di antaranya adalah Montesquieu(1689-1755), Voltaire (1694-1778), E. de Condillac (1715-1780), P. d’ Holbach (1723-1789), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dan Condorcet (1743-1794). Di Jerman Pencerahan berjalan lambat. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat dan politiknya yang masih feodal pada masa itu, serta pemikiran rasionalisme yang sangat kuat pengaruhnya pada dunia akademik. Aliran yang dominan di Jerman pada waktu itu adalah rasionalisme Leibniz yang disebarluaskan oleh Christian Wolff (1679-1750) serta para pengikutnya. Wolff menafsirkan pemikiran Leibniz dengan cara yang sangat sistematis. Pada abad ke 18, filsafat Leibniz-Wolffian menjadi kurikulum standar di seluruh universitas Jerman. Tentu saja kritik dari berbagai pemikiran lainnya terhadap sistem pemikiran tersebut juga ada. Salah satunya adalah C. A Crussius (1715-1775). Ia menulis buku yang berjudul Popularphilosophie, yang merupakan kritik tajam terhadap rasionalitas Leibniz-Wolffian. Buku Popularphilosphie, tulis Kant dalam Kritik Atas Rasio Murni, secara megah menggambarkan bagaimana orang bisa berpikir secara bebas.[11] Akan tetapi kritik tersebut masih tidak mampu membendung dominasi rasionalisme di Jerman pada waktu itu. Dengan kata lain rasionalisme Leibniz sama sekali tidak menemukan lawan tanding pemikiran yang seimbang sampai Kant menuliskan Kritik Atas Rasio Murni pada akhir abad ke 18. Pada waktu Kant menulis buku tersebut,, semangat Pencerahan mulai menurun. Setelah abad ke 18, para filsuf mulai berpikir bahwa humanisme universal, yang menjadi tesis dasar para pemikir Pencerahan, juga mempunyai sisi negatif, dan sisi negatifnya itu ternyata sangat besar. Humanisme universal di sini adalah paham yang menekankan bahwa semua manusia itu memiliki harkat dan martabat yang setara, serta mampu untuk menentukan sikap dan pendapat mereka secara otonom dengan mengacu pada kapasitas rasio manusia yang bersifat universal.[12]
Di dalam kerangka pemikiran skolastisisme, pengetahuan tentang Tuhan dan pengetahuan tentang Kosmos saling melengkapi satu sama lain, dan tidak bisa dipisahkan. Thomisme menggabungkan teologi Kristen dengan filsafat alam Aristoteles dalam satu kesatuan wacana. Pada sains hal ini tidak lagi berlaku. Para saintis memandang alam secara mekanis, matematis, dan sama sekali bertolak belakang dari filsafat alam Aristoteles yang melihat alam secara metafisis sebagai kesatuan antara forma dan materi. Sains modern pada waktu itu mulai memberi peran yang berbeda pada Tuhan di dalam analisis mereka atas alam. Tuhan tidak lagi dipahami sebagai Tuhan yang berpartisipasi membentuk kehidupan dan sejarah manusia, tetapi Tuhan yang menciptakan dunia berdasarkan hukum-hukumnya, dan kemudian tidak lagi berpartisipasi di dalam dunia. Inilah yang disebut sebagai Deisme. Konsekuensinya agama pun mulai kehilangan legitimasinya, dan ditinggalkan. Akan tetapi beberapa pemikir Pencerahan tidak siap untuk menganut ateisme, dan lebih memilih untuk bersikap kritis terhadap Gereja Katolik dan Protestan pada waktu itu. Jadi para pemikir Pencerahan juga memiliki kecenderungan untuk memberikan landasan rasional terhadap agama. Hal inilah yang terjadi di Jerman, di mana tanda-tanda penolakan terhadap agama hampir tidak terlihat. Di Perancis para philosophes melakukan kritik tajam terhadap agama, dan kemudian menganut ateisme. Lepas dari perbedaan di antara mereka, para pemikir Pencerahan mengajukan satu pertanyaan yang sama, bagaimana pengetahuan akan alam dan pengetahuan akan Tuhan dapat disintesiskan? Salah satu jawaban yang dirumuskan adalah tanda bahwa alam ini memiliki keteraturan sudah merupakan bukti bagi eksistensi Tuhan. Tatanan alam yang sudah begitu teratur ini merupakan bukti nyata bagi eksistensi Tuhan. Akan tetapi penjelasan ini sama sekali tidak memuaskan, terutama bagi kalangan teolog, karena tidak sesuai dengan ajaran Kitab Suci. Sementara itu Deisme yang berpendapat bahwa Tuhan telah menciptakan alam dengan hukum-hukumnya, dan kemudian Ia tidak berperan serta lagi, terlalu kering bagi iman Kristiani yang meyakini Tuhan berperan langsung di dalam sejarah manusia. Di samping itu deisme juga menolak wahyu yang justru menjadi sentral di dalam teologi Kristiani. Konflik antara sains dan agama pun tidak terelakkan lagi. Metafisika yang tadinya dianggap sebagai penjaga rasionalitas dan pengetahuan manusia secara keseluruhan kini mengalami keterpecahan dan kritik tajam dari berbagai penjuru.
Tegangan antara para pemikir yang masih mempertahankan agama di satu sisi dan para ilmuwan sains di sisi lain mengkristal di dalam salah satu korespondensi yang ditulis oleh Leibniz pada 1717. Memang Leibniz dan Newton sama-sama mewakili kedua belah pihak yang saling berdebat. Mereka banyak berdebat di sekitar problematika bagaimana tepatnya manusia bisa mengetahui dunianya. Leibniz lebih memilih menggunakan metode deduktif. Metode ini terinspirasi dari Rene Descartes (1596-1650) yang menggunakan model matematika. Model ini dimulai dengan prinsip-prinsip abstrak dan kemudian bergerak ke perumusan konkret. Kontras dengan itu Newton menggunakan metode induktif yang dimulai dari pengukuran kuantitatif dari fenomena yang ingin diselidiki, dan kemudian sampai pada prinsip-prinsip umum.[13] Di dalam korespondensinya Leibniz berpendapat, bahwa model yang dikembangkan Newton tidaklah sesuai dengan prinsip rasionalitas yang mampu mengabstraksikan alam ke dalam prinsip-prinsip utama. Sementara Newton sendiri berpendapat, bahwa model yang digunakannya adalah model saintifik yang sah secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian kedua pendekatan ini sangatlah berbeda, dan bahkan bertentangan. Metafisika, yang dirumuskan oleh Leibniz, dan sains, yang dirumuskan oleh Newton, tampak saling berkontradiksi satu sama lain. Sekali lagi metafisika tampak kembali dipertanyakan kredibilitasnya.
Di sisi lain tesis yang paling ‘mengguncang’ filsafat, terutama epistemologi dan metafisika, pada waktu itu adalah skeptisisme empiris yang dirumuskan oleh David Hume. Keyakinan bahwa rasio manusia telah secara langsung memiliki kesesuaian dengan alam telah menjadi suatu anggapan banyak diterima oleh para pemikir Pencerahan. Humelah yang menolak tesis tersebut. Menurutnya ‘kepercayaan’ kita tentang adanya hukum-hukum di dalam alam tidak memiliki landasan rasional yang cukup memadai, sehingga pemahaman kita selama ini didasarkan tidak lebih hanya kepada ‘kebiasaan-kebiasaan’ semata. Hukum alam dengan demikian tidak lebih dari sekedar ‘kebiasaan’ yang telah sering kita lihat sebelumnya. Lebih dari itu Hume berpendapat, bahwa apa yang disediakan alam dan kemudian kita percayai sebagai suatu ‘kebiasaan’ hanya dapat diketahui melalui pengalaman. Dengan demikian kepercayaan religius sama sekali tidak mempunyai tempat. Metafisika spekulatif pun juga tidak mendapatkan tempat. “Setiap bentuk refleksi filsafat metafisis”, demikian tulis Hume, “haruslah kita buang ke dalam api! Karena itu mengandung tidak lebih dari sekedar ilusi.”[14] Kesimpulan yang dirumuskan oleh Hume tersebut bisa kita cap sebagai paradoks, karena ia mengkritik metafisika dengan merumuskan metafisika baru, yakni metafisika yang didasarkan pada pengalaman. Yang jelas pada saat itu, Hume segera membutuhkan sebuah tanggapan dari para pemikir di jamannya.
Secara khusus dalam bidang refleksi epistemologi, Kant hendak merumuskan sebuah jembatan raksasa untuk membuat sintesis antara rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio saja. Pengalaman empiris hanya menegaskan apa yang telah sebelumnya telah diketahui oleh rasio. Empirisme persis berpendapat sebaliknya: hanya segala sesuatu yang merupakan pengalaman inderawi sajalah yang bisa dijadikan sebagai dasar pengetahuan manusia. David Hume berdasarkan pandangan ini berpendapat bahwa semua hal yang tidak dapat diketahui secara inderawi manusia adalah suatu bentuk kepercayaan saja, dan tidak bisa dijadikan pengetahuan yang sahih. Prinsip kausalitas misalnya bukanlah merupakan suatu kepastian, tetapi kemungkinan, yang didapatkan dari kebiasaan manusia saja.[15] Di samping Hume para pemikir empirisme lainnya adalah Locke dan Berkeley. Mereka berargumentasi bahwa pengetahuan manusia berasal sepenuhnya dari pengalaman inderawi. Locke misalnya sangat menekankan pentingnya pengalaman inderawi untuk menginformasikan kepada apa yang sesungguhnya menjadi obyek pada dirinya sendiri. Ia juga berpendapat bahwa pikiran manusia adalah suatu kertas kosong, sebuah tabula rasa, yang diisi oleh ide melalui interaksinya dengan dunia. Pengalaman inderawi akan dunia mengajarkan semuanya, termasuk konsep identitas, sebab akibat, dan sebagainya. Kant sendiri nantinya berpendapat bahwa tesis tentang pikiran sebagai tabula rasa ini tidaklah cukup untuk menjelaskan tentang kemampuan kita mengetahui obyek pengetahuan. Artinya ada suatu komponen di dalam pikiran kita yang memungkinkan kita mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman inderawi.
Di sisi lain Berkeley merumuskan fenomenalisme (phenomenalism). Berlawanan dari pemikiran Locke, ia mengajukan semacam tanggapan kritis terhadap paham yang berpendapat bahwa indera kita mampu mengetahui obyek yang berada independen dari pikiran kita. Karena pikiran manusia hanya dapat mengetahui obyek yang dapat ditangkap oleh inderanya, demikian argumentasi Berkeley, maka manusia tidak dapat mengetahui obyek yang berada independen dari pikiran mereka. Lebih dari itu ia bahkan berpendapat bahwa obyek yang bersifat independen dari pikiran manusia sama sekali tidak dapat diketahui. Dari perspektif filsafat Kant, pemikiran Berkeley disebut juga sebagai idealisme material, yakni pandangan bahwa kita tidak dapat mengetahui obyek material yang ada di luar diri kita. Bagi Berkeley obyek material yang bersifat independen terhadap pikiran tidaklah dapat diketahui. Pengalaman inderawi hanya mampu menangkap gambaran-gambaran mental, dan bukan benda pada dirinya sendiri. Ia berpendapat bahwa penilaian kita akan suatu obyek adalah sungguh-sungguh hanya merupakan penilaian terhadap gambaran-gambaran mental (mental images) ini, dan bukan subtansi yang memungkinkan gambaran-gambaran mental itu untuk ada.
David Hume menegaskan apa yang sebelumnya telah dirumuskan oleh Berkeley dengan mempertanyakan seluruh kepercayaan-kepercayaan akal sehat kita tentang sumber pengetahuan manusia. Ia berpendapat bahwa kita tidak dapat mengandaikan adanya justifikasi apriori ataupun aposteriori tentang beberapa kepercayaan fundamental akal sehat kita, seperti prinsip kausalitas yang menyatakan bahwa semua kejadian pasti memiliki sebab. Dengan tesis Hume tersebut, maka semakin jelaslah bahwa empirisme tidak dapat memberikan kita justifikasi epistemologis (epistemological justification) untuk semua klaim kausalitas yang selama ini dianggap tepat dan andaikan begitu saja.[16]
Kant sangat tidak setuju dengan semua pemikiran yang bersifat skeptis di atas. Di dalam bukunya yang berjudul Kritik atas Rasio Murni, ia mengajukan argumentasi-argumentasi untuk menunjukkan ketidaktepatan argumentasi para pemikir empiris, seperti Locke, Berkeley, dan Hume, karena semua refleksi dan analisis mereka mengandaikan hal-hal yang dalam pemikiran mereka justru ditolak. Bahkan setiap bentuk pengetahuan yang dapat kita ketahui haruslah mengandaikan klaim-klaim tersebut, dan tidak bisa tidak. Meskipun menaruh simpati besar terhadap refleksi para pemikir empirisme, ia tetap tidak puas dengan argumentasi mereka yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman inderawi.
Para pemikir rasionalis seperti Descartes, Spinoza, dan Leibniz, mendekati problematika yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi mereka pengetahuan tentang dunia luar, tentang jiwa, tentang diri, tentang Tuhan, etika, serta sains adalah ide yang sudah pasti berada inheren di dalam pikiran. Leibniz berpendapat bahwa dunia sudah dapat diketahui secara apriori melalui analisis ide-ide dan turunan atasnya secara logis. Pengetahuan dapat diperoleh cukup dengan menggunakan rasio saja. Pernyataan Descartes “aku berpikir maka aku ada” jelas menggambarkan kebenaran yang sangat diyakini oleh para pemikir rasionalis ini. Dengan berbekal pengetahuan yang pasti tentang keberadaan dirinya sendiri, Descartes berharap mampu membangun sebuah dasar yang kokoh bagi semua bentuk pengetahuan manusia. Baginya pengetahuan tentang obyek yang berada di luar dirinya adalah kombinasi antara kesadaran akan keberadaan dirinya sendiri (res cogitans dan res extensa) dan argumen bahwa Tuhan itu ada, serta tidak menipunya dengan semua bentuk pengetahuan yang masuk melalui indera.
Kant juga banyak menyanggah argumentasi para pemikir rasionalis di dalam salah satu bagian Kritik atas Rasio Murni, yakni bagian antinomi-antinomi. Salah satu antinomi adalah tentang dunia. “Dunia memiliki awal di dalam waktu dan terbatas di dalam ruang” yang dihadapkan dengan argumen “Dunia tidak memiliki awal dan tidak terbatas di dalam ruang.”[17] Ia berpendapat bahwa kedua argumen ini melambangkan kesalahpahaman metafisis di dalam seluruh pemikiran rasionalisme. Kedua argumen di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena keduanya beranggapan bahwa benda-pada-dirinya-sendiri dapat diketahui, yakni dunia sebagai benda-pada-dirinya-sendiri. Menurut Kant antinomi dapat dihilangkan, jika kita sungguh mengerti fungsi dan kapasitas sesungguhnya dari fakultas rasio kita yang berperan dalam menciptakan pengetahuan. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengetahui benda-pada-dirinya-sendiri, dan bahwa pengetahuan kita terbatas pada obyek yang dapat dialami secara inderawi. Proyek filsafat rasionalisme gagal, karena para pemikirnya tidak mempertimbangkan peran pengalaman empiris di dalam mengkonstruksi pengetahuan. Memang refleksi filosofis mereka tentang pengetahuan dapat menjelaskan beberapa aspek tentang isi dari pengetahuan kita. Akan tetapi mereka tidak akan mampu memberikan argumentasi yang koheren tentang klaim-klaim metafisis yang mereka rumuskan, baik itu tentang Tuhan, tentang Dunia, ataupun tentang Jiwa. Metafisika yang dibangun mereka inilah yang menjadi obyek kritik Kant nantinya. Walaupun ia sendiri nantinya akan terjebak pada pemikiran yang bersifat metafisis juga.[18]
Kant memilih menggunakan kata Kritik (critique) untuk buku-buku yang ditulisnya. ‘Kritik’ disini tidak melulu dimaksudkan sebagai evaluasi negatif akan suatu obyek tertentu, tetapi sebagai suatu refleksi kritis, dan hasilnya bisa saja positif, tetapi juga bisa negatif.[19] Kata ‘murni’ (pure) adalah term teknis yang digunakan oleh Kant, dan berarti bahwa sesuatu itu tidak mengandung apapun yang berasal dari pengalaman inderawi. ‘Rasio’ disini juga dikatakan dalam arti teknis, yakni sebagai fakultas konseptual di dalam dimensi kognitif kita yang membantu kita memaknai pengalaman, namun tidak didapatkan dari pengalaman inderawi. Dalam bahasa Kant elemen konseptual tersebut bersifat apriori. Dengan demikian Kritik atas Rasio Murni adalah suatu penyelidikan filosofis (philosophical enquiry) terhadap fakultas kognitif kita untuk mengetahui realitas. Cara yang ditempuh yakni dengan pertama-tama membedakan antara rasio murni (pure reason) dengan pengalaman inderawi (sense experience), dan kemudian melihat sejauh mana rasio kita mampu mengetahui hal-hal yang berada di luar pengalaman inderawi, seperti Tuhan dan Jiwa.[20] Penilaian apakah kita dapat mengetahui obyek-obyek yang berada di luar pengalaman inderawi dilakukan oleh Kant pada setengah bagian kedua buku Kritik atas Rasio Murni, yakni setelah ia memberikan argumentasi yang mendetil tentang kondisi-kondisi apriori yang memungkinkan terjadinya pengetahuan.
Argumentasi Kant memang tampak membingungkan, karena ia seolah menggunakan argumentasi yang lebih mengutamakan peran unsur apriori daripada kapasitas kognitif manusia. Memang klaim semacam itu tidak dapat dari ruang hampa, tetapi sudah selalu didukung oleh beberapa argumentasi yang cukup memadai. Ia menghabiskan banyak halaman di dalam buku Kritik atas Rasio Murni untuk membuktikan bahwa aspek kognitif manusia hanya mampu memproduki pengetahuan, jika ada pengandaian-pengandaian apriori yang sudah dipegang terlebih dahulu. Jika pengandaian apriori itu tidak ada, maka pengetahuan menjadi tidak mungkin.
Di dalam bagian preface buku itu, Kant sangat yakin bahwa proses ‘pengadilan’ terhadap rasio itu akan mampu menyelesaikan berbagai problem metafisika yang ada sebelumnya.[21] Hasil dari proses itu akan membuktikan, bahwa rasio manusia mampu mengetahui obyek yang berasal dari pengalaman inderawi, tetapi bukan obyek yang di luar pengalaman inderawi. Inilah inti kritik atas metafisika yang dirumuskannya. Salah satu cara yang ditempuhnya untuk menyelesaikan problem metafisis adalah dengan merumuskan semacam dasar guna membedakan antara penggunaan kapasitas rasio manusia yang legitim, dan penggunaannya yang tidak legitim. Dasar ini adalah pengalaman inderawi. Artinya penggunaan rasio manusia menjadi sah, ketika diterapkan pada obyek yang dapat diketahui melalui pengalaman inderawi. Sebaliknya penggunaan rasio manusia menjadi tidak sah, ketika diterapkan untuk mengetahui obyek yang tidak dapat dialami secara inderawi. Batas-batas pengetahuan manusia, dengan demikian, adalah batas-batas pengalamannya. Apa yang dapat diketahui adalah apa yang dapat dialami secara inderawi, dan apa yang tidak dapat dialami secara inderawi tidaklah dapat diketahui. Akan tetapi disinilah letak ambiguitas argumentasi Kant, ia ingin membela metafisika dengan berpendapat bahwa metafisika diperlukan untuk memberikan kerangka pada pengetahuan. Dengan kata lain pengalaman inderawi dapat menjadi pengetahuan, karena adanya prinsip-prinsip apriori yang bersifat metafisis, yakni yang tidak dapat dialami. Bahkan rasio manusia selalu memiliki kecenderungan untuk bertanya tentang hal-hal yang tak terkondisikan, yakni kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan metafisis. Akan tetapi ia kemudian menolak penggunaan rasio manusia untuk merefleksikan entitas-entitas yang berada di luar pengalaman inderawi, seperti refleksi tentang Tuhan, atau tentang Jiwa. Metafisika yang menjadi sasaran kritik Kant adalah metafisika tradisional, yakni pemikiran spekulatif yang bersifat transenden (trancendent experience metaphysics).[22] Ia justru membela metafisika yang bersifat imanen yang memungkinkan pengalaman diolah menjadi pengetahuan, yakni metafisika pengalaman (metaphysics of experience).[23] Dengan demikian, metafisika pengalaman mungkin, tetapi metafisika transenden tidaklah mungkin.
Struktur dari Kritik atas Rasio Murni
Jika kita sekilas melihat susunan buku Kritik atas Rasio Murni, kita akan mendapat kesan bahwa buku itu adalah buku yang sangat kompleks, pengaturannya tidak transparan, dan setiap judul dari bab-bab yang ada di dalamnya tidak banyak menggambarkan isi dari bab. Memang arsitektur buku tersebut sungguh menggambarkan kerumitan pemikiran filsafatnya.
Tiga ‘pilar’ utama dari buku itu adalah Transcendental Aesthetic, Transcendental Analytic, dan Transcendental Dialectic. Setiap bagian mengacu pada kapasitas rasio manusia yang berbeda dimensi dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda pula. Bagian Aesthetic berkaitan dengan sensibilitas (kemampuan memperoleh pengalaman inderawi melalui intuisi, atau pengetahuan langsung), matematika, dan dengan geometri. Bagian ini mencakup pula analisis Kant tentang ruang dan waktu. Sementara itu bagian Analytic lebih banyak menganalisis tentang problem pemahaman (understanding), metafisika pengalaman (metaphysics of experience), dan ilmu-ilmu alam (natural science). Bagian Dialectic menganalisis kapasitas maksimal dari rasio manusia dan metafisika transenden (trancendent metaphysics). Bab ini terdiri dari tiga bagian, yakni metafisika tentang jiwa yang disebut Kant sebagai psikologi rasional (rational psychology), metafisika tentang dunia sebagai keseluruhan yang disebutnya sebagai kosmologi rasional (rational cosmology), dan tentang Tuhan yang disebutnya sebagai teologi rasional (rational theology).
Baik Analytic, Aesthetic, dan Dialectic berada pada bagian besar Trancendental Doctrine of Elements, karena masing-masing mengacu pada ‘elemen’ rasio yang berbeda. Aesthetic pada apa yang disebut Kant sebagai intuisi, Analytic pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan Dialectic dengan apa yang disebutnya sebagai ide-ide regulatif (regulative ideas). Apa yang biasa dimengerti sebagai intelek kini dipisahkan olehnya menjadi pemahaman (understanding) dan rasio (reason). Bagian yang lebih pendek, yakni Trancendental Doctrine of Method, menyediakan pendasaran epistemologi dan metafisis bagi Kritik atas Rasio Murni dengan refleksi atas metode pendekatannya. Di dalamnya ada bagian The Canon of Pure Reason yang memberikan penegasan terhadap seluruh sistem filsafat kritis di dalam buku tersebut.
Pengaturan bab-bab di dalam buku Kritik atas Rasio Murni dapat dimengerti lebih jelas, jika kita mengerti kesimpulan yang ditarik Kant tentang seluruh buku tersebut. Ada dua kesimpulan besar. Di satu sisi Aesthetic dan Analytic selalu berkaitan dengan obyek yang dapat diketahui. Dan di sisi lain, Dialectic berkaitan dengan obyek yang tidak dapat diketahui. Aesthetic dan Analytic lebih bersifat positif, karena lebih bertujuan untuk membuktikan bahwa kita dapat mengetahui obyek yang dapat dialami secara inderawi. Aesthetic banyak menganalisis pengalaman inderawi, terutama tentang kemungkinan pengetahuan akan obyek-obyek yang berada di dalam ruang dan waktu. Analytic lebih berada di level konseptual, termasuk tentang kategori subtansi dan kausalitas yang memungkinkan pengalaman diolah menjadi pengetahuan konseptual. Kedua bagian ini disebut juga sebagai metafisika pengalaman (metaphysics of experience). Sementara itu bagian Dialectic lebih bersifat negatif, karena lebih bertujuan untuk membuktikan bahwa kita tidak dapat mengetahui obyek-obyek yang berada di luar pengalaman inderawi kita. Bagian ini mau menolak legitimasi metafisika, terutama metafisika transenden (trancendent metaphysics). Dari dua tipe metafisika ini, kita dapat mengenali ambiguitas kritik atas metafisika yang dirumuskan Kant. Ia menolak metafisika transenden, tetapi mengafirmasi metafisika pengalaman. Metafisika pengalaman ini paling jelas terdapat pada bagian Analytic.
Dari pemaparan pada bab ini, kita dapat menarik setidaknya dua kesimpulan terkait dengan metode yang digunakan oleh Kant di dalam berfilsafat. Yang pertama adalah metode kritis untuk mencari kondisi-kondisi kemungkinan dari pengetahuan manusia. Kant tidak percaya begitu saja, bahwa manusia bisa mengetahui dunia luar. Maka itu ia menyelidiki terlebih dahulu, kondisi-kondisi macam apakah yang diperlukan, supaya manusia bisa sampai pada pengetahuan konseptual. Di dalam proses pencarian, ia menemukan setidaknya dua faktor, yakni kondisi-kondisi a priori di dalam pikiran manusia, dan benda-benda obyektif. Yang penting bagi kita adalah cara berpikir untuk mencari kondisi-kondisi kemungkinan dari keberadaan obyek yang kita pikirkan.
Yang kedua adalah upaya Kant untuk menempatkan persoalan moralitas pada akal budi. Kant tidak melulu melompat ke dalam penjelasan-penjelasan teologis-agamis untuk menjelaskan fenomena moral manusia, melainkan berusaha menemukan pendasaran rasional atasnya. Metode pencarian dasar rasional itulah yang bisa dijadikan contoh untuk penyelidikan obyek-obyek lainnya, terutama yang terkait langsung dengan dimensi hakiki manusia. Dua metode yang diajarkan Kant, yakni metode pencarian kondisi-kondisi kemungkinan dan metode pencarian dasar rasional atas fenomena yang ingin diteliti, akan menjadi dasar bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan selanjutnya.***
[1] Lihat Jill Vince Buroker, Kant’s Critique of Pure Reason, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, dan Reza A.A Wattimena, Pengandaian-pengandaian Metafisis di dalam Kritik Immanuel Kant terhadap Metafisika: Mempertimbangkan Kritik Karl Ameriks atas Kritik Immanuel Kant terhadap Metafisika, Jakarta, STF Driyarkara, 2009 (Tidak dipublikasikan).
[2] Lihat, Buroker, 2006, hal. 6.
[3] Kant, Critique of Pure Reason, 1998, Aviii, hal. xxiii. Seluruh kerangka sub bab ini diinspirasikan dari pembacaan saya atas tulisan Sebastian Gardner, 1999, hal. 1-26. Kutipan dari tulisan Kant juga diambil dari tulisan Gardner ini.
[4] Ibid “…metaphysics is perpetually brought to a stand…”
[5] Ibid, dan lihat Gardner, 1999, hal. 1. “Ever and again, we have to retrace our steps…”
[6] Kant, Bxv. “The degree and quality of disagreement in metaphysics makes it a ‘battle ground, a site of ‘mock-combats’ in which ‘no participant has ever yet succeeded in gaining even so much as an inch of territory…”
[7] Bdk, Ibid. “…The peculiar instability of metaphysics stands in stark contrast to the security of mathematics and natural science, and leaves us with no choice but to conclude that metaphysics ‘has hitherto been a merely random grouping..”
[8] Ibid, Bxvi “…Hitherto it has been assumed that all our knowledge must conform to objects’, but since this assumption has conspicuously failed to yield any metaphysical knowledge, we ‘must therefore make trial whether we may not have more success in the tasks of metaphysics, if we suppose that objects must conform to our knowledge…we should than proceeding on the lines Copernicus primary hypothesis’, this being the hypothesis of heliocentrism…”
[9] Lihat, Gardner, 1999, hal. 2. “…this chapter traces the route which Kant arrived at his view that metaphysics constitutes a problem, and his view of what exactly the problem of metaphysics consist in..”
[10] Kant, Axi[n], dalam Gardner, ibid, “our age is, en special degree, the age of criticism, and to criticism everything must submit. Religion through its sanctity, and law-giving through its majesty, may seek to exempt themselves from it. But they then awaken just suspicion, and cannot claim the sincere respect which reason accords only to that which has been able to sustain the test of free and open examination.”
[11] Ibid, Bxiii, hal. xxxi., “…C.A Crucius… submitted the wolffian school to sharp criticism, and it later lost ground to popularphilosophie, an eclectic, intellectually flaccid movement hostile to its esotericism (dismissed…as a pretentiously free manner of thinking…)”
[12] Lihat, http://en.wikipedia.org/wiki/Humanism
[13] Lihat, Gardner, 1999, hal. 5. “Leibniz employed a deductive method, derived from Rene Descartes… and modeled on mathematics, which began with abstract general notions and worked down to concrete nature; Newton by contrast ascended from quantitative measurement of the phenomena of the first principles.”
[14] Lihat, Gardner, 1999, hal. 6. “…Every… school of metaphysics…should commit to the flames…”
[15] Bdk, Tjahjadi, 2004, hal. 281. “Adanya sebuah prinsip kausalitas, misalnya, tidak bisa diterima sebagai sebuah prinsip karena tidak bisa diindra. Dengan demikian, filsafat dan ilmu pengetahuan alam yang cara kerjanya mengandalkan prinsi-prinsip yang tidak bisa mencapai kepastian, namun hanya kemungkinan.”
[16] Lihat, Tjahjadi, hal. 281. “Adapun empirisme berpendapat sebaliknya. Sumber pengalaman hanyalah pengalaman inderawi sehingga hanya yang bisa diindra saja yang bisa dijadikan dasar pengetahuan. Berdasarkan pandangan ini, Hume, misalnya, mengatakan bahwa semua hal yang tidak bersifat inderawi hanya bisa diperkirakan atau diterima sebagai kepercayaan saja, tetapi tidak bisa dipastikan.”
[17] Kant, 1998, A426/B 454 dalam http://www.iep.utm.edu/k/kantmeta.htm, “The First Antinomy argues both that the world has a beginning in time and space, and no beginning in time and space. The Second Antinomy’s arguments are that every composite substance is made of simple parts and that nothing is composed of simple parts. The Third Antinomy’s thesis is that agents like ourselves have freedom and its antithesis is that they do not. The Fourth Antinomy contains arguments both for and against the existence of a necessary being in the world. The seemingly irreconcilable claims of the Antinomies can only be resolved by seeing them as the product of the conflict of the faculties and by recognizing the proper sphere of our knowledge in each case. In each of them, the idea of "absolute totality, which holds only as a condition of things in themselves, has been applied to appearances"
[18] Uraian ini didasarkan pada pembacaan saya atas http://www.iep.utm.edu/k/kantmeta.htm
[19] Lihat, Ibid, Bxxv-xxvi, dalam Gardner, 1999, hal. 23. “Critique does not for Kant imply a negative evaluation of its object: it means simply a critical enquiry, the results of which may equally be positive.”
[20] Lihat, Ibid, Axii. Dalam Gardner, ibid, “So a critique of pure reason is a critical enquiry into our capacity to know anything by emplying our reason in isolation, i.e, without conjoining reason with sense experience; more specifically, it enquires into our capacity to know things lying beyond the bounds of sense experience, such as God and the Soul…”
[21] Lihat, Ibid, “…Kant gives firm indications in the Preface of the results that the tribunal will reach, and of the means by which the problem of metaphysics will be solved…”
[22] Lihat, Gardner, 1999, hal. 24. “The metaphysics that Kant attacks, charateristic of rationalism, is speculative or transcendent…, and that which he defends is immanent…., or the metaphysics of experience….”
[23] Lihat pemaparan menarik tentang proyek kritik Kant terhadap metafisika tradisional di dalam http://plato.stanford.edu/entries/kant-metaphysics/, “How are synthetic a priori propositions possible? This question is often times understood to frame the investigations at issue in Kant’s Critique of Pure Reason. In answer to it, Kant saw fit to divide the question into three: 1) How are the synthetic a priori propositions of mathematics possible? 2) How are the synthetic a priori propositions of natural science possible? Finally, 3) how are the synthetic a priori propositions of metaphysics possible? In systematic fashion, Kant responds to each of these questions. The answer to question one is broadly found in the Transcendental Aesthetic, and the doctrine of the transcendental ideality of space and time. The answer to question two is found in the Transcendental Analytic, where Kant seeks to demonstrate the essential role played by the categories in grounding the possibility of knowledge and experience. The answer to question three is found in the Transcendental Dialectic, and it is a resoundingly blunt conclusion: The synthetic a priori propositions that characterize metaphysics are not “really” possible at all. Metaphysics, that is, is inherently dialectical. Kant’s Critique of Pure Reason is thus as well known for what it rejects as for what it defends. Thus, in the Dialectic, Kant turns his attention to the central disciplines of traditional, rationalist, metaphysics — rational psychology, rational cosmology, and rational theology. Kant aims to reveal the errors that plague each of these fields.”