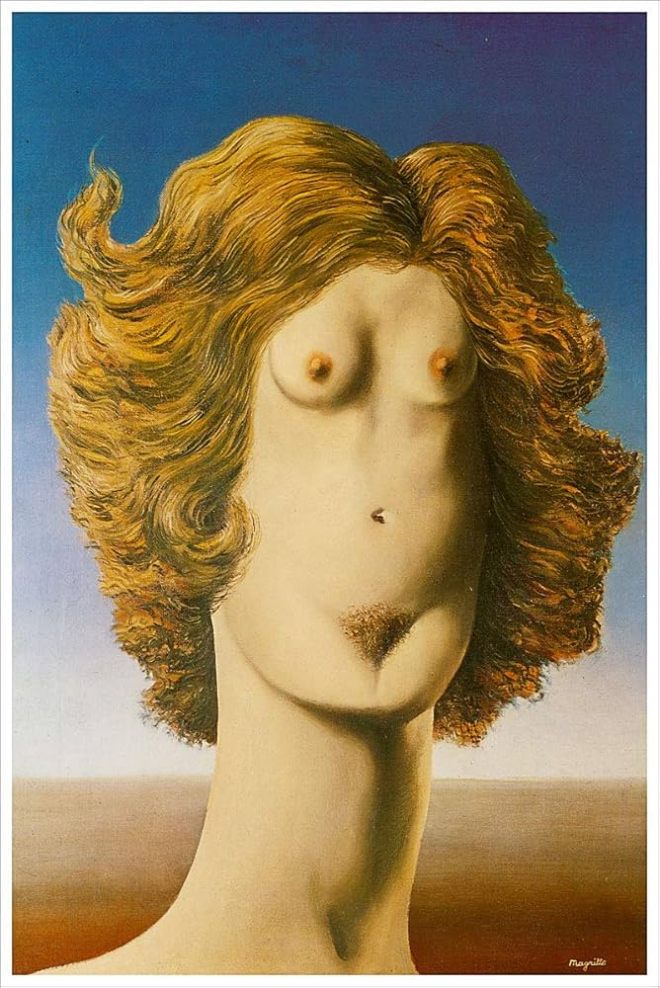Oleh Dhimas Anugrah, Penulis buku “Filosofi Kematian” (Kanisius, 2024) dan Ketua Circles Indonesia, komunitas pembelajar di bidang budaya, filsafat, dan sains.
Delapan puluh tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah rahmat yang patut kita rayakan. Bukan hanya lewat upacara seremonial tentunya, tapi juga melalui perenungan filosofis yang agak mendalam. Sejarah bangsa ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dibentuk oleh arah dasar keberadaan manusia sebagai makhluk yang mencari makna.
Dalam filosofi eksistensial, Martin Heidegger memperkenalkan konsep Sein zum Tode, atau berada menuju kematian, yaitu kesadaran bahwa manusia sepanjang hidupnya selalu bergerak menuju akhir. Eksistensi manusia tak bisa dilepaskan dari kefanaan. Heidegger menyatakan bahwa manusia yang sadar akan keberadaannya “selalu telah menuju akhirnya” (Being and Time, 1962). Lanjutkan membaca Kemerdekaan dan Panggilan Mencintai